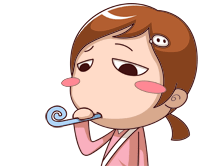Kami hanya terpekur, diam dan tak sepatah kata pun keluar dari mulut kami. Semuanya hening seolah kosong. Namun, masih terasa gurat-gurat kekesalan yang memuncak dan nafas naik turun pertanda menahan amarah yang teramat sangat. Jam dinding sudah menunjukkan waktu yang tak efisien untuk bicara. Suara-suara kendaraan di luar sana pun hanya sesekali melintas. Suara jangkrik mulai terdengar lamat-lamat diselingi tukang nasi goreng yang tengah asik meracik di atas bara api.
Kuperhatikan ia diam-diam melalui sudut mataku. Kulihat gurat-gurat penuaan di wajahnya. Pancaran rasa pedih dan perjuangan yang panjang. Kutatap kedua bola matanya, lalu rambutnya yang kian hari kian memutih dan tubuhnya yang tak lagi setegap dulu.
Kemudian, ku dengar suara kursi bergeser. Kulihat ia merubah posisi duduknya, tanpa merubah ekspresi di wajahnya yang masih sama; kesal. Hanya saja, kini kutebak ia akan kembali membuka pembicaraan kami yang sempat terputus perdebatan panjang. Desah nafasnya mulai kudengar, kupahami itu sebagai persiapannya untuk menataku kata untuk ia sampaikan padaku.
“Lalu apa keputusanmu sekarang?”, tanyanya tiba-tiba. Ku jawab sigap, lantang dan tanpa keraguan, “saya ingin berhenti”. Masih dengan intonasi yang sama ia kemudian bertanya lagi, “kamu yakin dengan keputusanmu?, kamu tak ingin berpikir ulang?”. Tapi, kali ini hanya kujawab dengan anggukkan kepala.
Tak ada lagi suara balasan. Yang ada hanya langkah-langkah kaki menuju kamar pribadinya, tanpa sedikitpun kata lanjutan. Aku paham, kalau sudah begini, pertanda ia sama sekali tak setuju dengan keputusan yang aku ambil ini. Ku ambil nafas panjang, berpikir ulang dan kembali menuliskan rencana apa yang akan kulakukan bila benar aku yakin akan berhenti.
Ia yang kumaksud adalah seorang lelaki berusia setengah abad yang hingga kini kukenal dan kupanggil dengan sebutan bapak. Ia yang sedari dulu mengusahakan apapun yang terbaik bagi hidupku, ibuku dan kedua adikku. Ia yang hanya lulusan SD (itu pun hanya sampai kelas dua) mampu menyekolahkan aku hingga perguruan tinggi hingga aku berhasil meraih gelar sarjana. Sebuah gelar pendidikan bahkan ia sendiri pun tak pernah mengecapnya.
Ia yang sedari kecil tak pernah merasakan hidup layak sebagaimana teman-temannya rasakan. Di usianya yang masih belia, ia harus bekerja menjadi kuli panggul di pasar guna membantu ayah ibunya yang juga kakek nenekku bekerja. Terkadang ia membawa serta ketiga adiknya mengais kepingan rupiah sambil menjajankan gorengan yang nenekku buat ke tiap lapak yang ada di pasar. Tak ada hari tanpa bekerja, hingga akhirnya ia pun memilih untuk meninggalkan bangku sekolah dan focus bekerja.
Karena itu pula lah, bapak sama sekali tak ingin aku, ibuku san kedua adikku merasakan hal yang sama seperti yang pernah ia alami. Meskipun, kami bukan keluarga “berada” tapi bapak selalu berusaha memberikan apapun yang terbaik untuk kami. Meski pada akhirnya ia harus banting tulang siang malam demi kami. Tak diijinkannya aku untuk tidak merasakan kebahagiaan sebagai seorang anak. Hidupku begitu bahagia meski dalam segala keterbatasan yang ada.
Aku ingat betul, ketika usiaku belum genap tiga tahun bapak selalu mengajakku berakhir pekan di alun-alun kota dan membelikannya aromanis. Kenapa aku tahu? Karena fotoku tengan memegang aromanis masih tersimpan rapi di album masa kecilku. Tapi tak bersama ibuku. Awalnya aku tak paham kenapa ibu tak diajak serta. Barulah kemudian aku tahu kalau saat itu ibulah yang menjadi tulang punggung keluarga kami.
Kurasakan kebahagian yang tak terhingga di hidup kami. Limpahan kasih sayang begitu banyak kudapat. Kebahagiaan kami semakin berlipat hingga suatu hari bapak di terima bekerja di tempat kakek sebelumnya bekerja. Kali ini waktuku lebih sering kuhabiskan bersama ibu. Terkadang diajaknya aku berpetualang di dapur atau sekedar menemaninya memasak. Kulihat ia begitu tulus merawatku serta berbakti terhadap bapak. Sungguh gambaran keluarga kecil nan harmonis yang selalu kutemukan di novel-novel yang aku baca.
Beliau begitu bangga ketika satu hari aku mengabarkan berita gembira padanya. Aku diterima bekerja di sebuah sekolah elit dan ternama di kota kami. Sekolah yang begitu mahal dan sulit dijangkau untuk kalangan bawah, namun memiliki kualitas pendidikan yang baik.
Tak kuduga ekspresi bapak yang begitu sumringah sekaligus bangga luar biasa. Dikabarkannya berita spektakuler ini pada semua orang, sampai aku malu dibuatnya. Intinya dengan aku bisa bekerja disana, bapak berpikiran aku merupakan satu diantara orang beruntung. Selain gaji yang mumpuni, secara pengalaman pun akan banyak yang aku dapat. Ditambah aku hanya seorang sarjana Sastra Inggris yang baru lulus satu tahun dan minim pengalaman. Sebuah prestasi luar biasa dan harus diapresiasi.
Ibu pun demikian, tak henti-hentinya beliau mengucap Alhamdulillah. Ah…rasanya begitu senang melihat orangtua begitu bahagia. Tak terbayar dan tak ternilai harganya.
Sampai lah kini, aku yang merupakan anak tertua, anak yang ia banggakan sekaligus juga diharapkan menjadi tulang punggung keluarga membuatnya kecewa untuk pertama kalinya. Harapannya seolah kandas oleh keputusan yang baru saja aku utarakan.
Kuputuskan berhenti saja dari pekerjaan ini. Bukan…bukan aku tak senang menjadi seorang guru. Sungguh inilah mimpi yang jadi kenyataan bisa menjadi seorang pendidik. Sekali lagi bukan itu alasannya. Ada kepuasan batin yang tak kudapat dengan bekerja disini. Ada banyak hal yang harus aku korbankan walau kompensasinya lembaran rupiah begitu mudah kudapat.
“Sungguh bapak tak habis pikir dengan jalan pikiranmu”, keluhnya. “Orang lain begitu sulit mendapatkan pekerjaan, eh..kamu malah mau keluar”, “orang yang sudah punya pekerjaan saja gajinya minim, lah..kamu gaji besar dan menjanjikan malah mau dilepaskan’. Serentetan pertanyaan bapak sampaikan padaku dengan intonasi yang sudah tak terkontrol lagi. Naik turun dan iramanya tak beraturan.
“Saya ingin berwirausaha pak”, ucapku tiba-tiba. Wajah bapak memerah, matanya terbelalak, tangannya ia kepalkan dan sekonyong-konyong melemparkan ijasah kuliahku. ‘Untuk apa bapak sekolahkan kamu tinggi-tinggi kalau pada akhirnya hanya jadi seorang pedagang?”, bentaknya. “Bapak saja dulu memilih berdagang karena tak ada pilihan yang lebih baik untuk bapak, tapi kamu….pekerjaan bagus, pendidikan tinggi malah mau berdagang!!!”, amarahnya kian tak terkendali.
Namun, kembali ia berkata dengan intonasi rendah dan berirama. “Bapak tak pernah melarangmu berdagang, berwirausaha atau apalah istilahnya. Tapi hanya sekedar sampingan, bukan profesi”, paparnya perlahan. Tapi aku tetap pada pendirianku. Keluar dan berwirausaha atau aku bertahan tapi bekerja tak sepenuh hati”.
Apa salahnya menjadi seorang wirausaha??
*Malam kian larut, gemericik hujan mulai mengalunkan simfoni alam.
Bandung, 26-11-2011